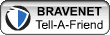Apakah Hak Tolak Wartawan Bersifat Mutlak?
oleh Ari Juliano Gema
Beberapa waktu lalu saya menonton sebuah episode sinetron “Dunia Tanpa Koma” yang biasanya ditayangkan di televisi setiap Sabtu malam. Pada episode sinetron yang berlatar dunia jurnalistik itu diceritakan bahwa tokoh Raya, seorang wartawati muda yang diperankan oleh Dian Sastro, berhasil mewawancarai tokoh Jendra yang sedang melarikan diri dari penjara karena kasus narkoba.
Singkatnya, hasil wawancara itu memunculkan perdebatan di majalah tempat Raya bekerja mengenai apakah hasil wawancara itu akan dimuat atau tidak, dengan mempertimbangkan aspek etika dan hukum. Namun akhirnya, tokoh “Boss Besar”, yang merupakan pimpinan tertinggi di majalah tempat Raya bekerja itu, memutuskan akan berkoordinasi dulu dengan pihak kepolisian sebelum memuat hasil wawancara itu, dengan tujuan untuk membantu pihak kepolisian dalam menemukan Jendra yang sedang buron.
Hak Tolak
Saya membayangkan seandainya keputusan si “Boss Besar” dalam sinetron itu diikuti juga di dunia nyata oleh para “Boss Besar” media cetak dan televisi yang menayangkan Dharmono K. Lawi, mantan Ketua DPRD Banten yang menjadi terpidana kasus korupsi dan berstatus buron sejak April 2006 lalu. Hal itu tentu tidak akan membuat Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh menjadi “uring-uringan” seperti sekarang ini. Hal yang membuat Jaksa Agung semakin “uring-uringan” adalah argumen dari kalangan media dan pakar hukum bahwa wartawan yang berhasil menemukan Dharmono punya hak untuk menolak mengungkapkan keberadaan Dharmono yang sedang buron itu apabila aparat penegak hukum meminta keterangan mengenai hal tersebut. Menurut mereka, hak itu diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) yang disebut sebagai Hak Tolak.
Berkenaan dengan hal itu, Jaksa Agung menyampaikan keprihatinannya terhadap wartawan yang “memburu” Dharsono hanya untuk kepentingan pemberitaan saja tapi tidak mau melaporkan keberadaan Dharsono itu kepada aparat penegak hukum. Padahal, menurut Jaksa Agung, setiap warga negara memiliki kewajiban hukum untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila mengetahui ada tindak kejahatan.
Aturan Hukum
Mengenai kewajiban hukum warga Negara berkaitan dengan keberadaan buronan itu, sebenarnya kita dapat melihat ketentuan Pasal 221 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang pada pokoknya mengatur bahwa barangsiapa yang dengan sengaja: (i) menyembunyikan pelaku kejahatan atau orang yang dituntut karena kejahatan; atau (ii) memberi pertolongan kepada pelaku kejahatan untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat yang berwenang, dapat dikenai sanksi pidana penjara maksimal sembilan bulan penjara.
Sedangkan dalam UU Pers diatur bahwa dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak, yaitu hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama dan/atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya. Hak tersebut dapat digunakan jika wartawan dimintai keterangan oleh pejabat penyidik dan/atau diminta menjadi saksi di pengadilan.
Kalau begitu, apakah seorang wartawan dapat menggunakan Hak Tolaknya untuk melindungi keberadaan seorang buronan? Menurut saya perlu dipertimbangkan latar belakang dari penggunaan Hak Tolak itu. Apabila memang buronan itu adalah sumber berita dari wartawan yang bersangkutan, maka wartawan itu dapat menggunakan Hak Tolaknya. Dengan demikian ketentuan Pasal 221 ayat (1) KUHP tidak dapat diberlakukan kepada wartawan yang menolak mengungkapkan keberadaan buronan yang menjadi sumber beritanya, karena hal itu dilindungi oleh UU Pers yang merupakan lex specialis dari KUHP.
Namun, apakah itu berarti Hak Tolak bersifat mutlak? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu melihat penjelasan mengenai Hak Tolak dalam UU Pers, yang mengatakan bahwa Hak Tolak dapat dibatalkan demi kepentingan dan keselamatan Negara atau ketertiban umum yang dinyatakan oleh pengadilan. Dengan demikian, sebenarnya Hak Tolak itu tidak bersifat mutlak.
Menimbang hal di atas, seharusnya saat ini Jaksa Agung tidak perlu patah semangat dalam mengejar buronan yang menjadi sumber berita wartawan itu, karena Jaksa Agung masih punya peluang untuk mendapatkan informasi mengenai keberadaan buronan itu. Jaksa Agung dapat meminta penetapan dari pengadilan untuk membatalkan Hak Tolak dari wartawan yang bersangkutan. Apabila setelah terbit penetapan pengadilan yang membatalkan Hak Tolaknya, wartawan yang bersangkutan masih juga menolak mengungkapkan keberadaan buronan itu, maka ketentuan Pasal 221 ayat (1) KUHP dapat dikenakan terhadap wartawan itu.
Beberapa waktu lalu saya menonton sebuah episode sinetron “Dunia Tanpa Koma” yang biasanya ditayangkan di televisi setiap Sabtu malam. Pada episode sinetron yang berlatar dunia jurnalistik itu diceritakan bahwa tokoh Raya, seorang wartawati muda yang diperankan oleh Dian Sastro, berhasil mewawancarai tokoh Jendra yang sedang melarikan diri dari penjara karena kasus narkoba.
Singkatnya, hasil wawancara itu memunculkan perdebatan di majalah tempat Raya bekerja mengenai apakah hasil wawancara itu akan dimuat atau tidak, dengan mempertimbangkan aspek etika dan hukum. Namun akhirnya, tokoh “Boss Besar”, yang merupakan pimpinan tertinggi di majalah tempat Raya bekerja itu, memutuskan akan berkoordinasi dulu dengan pihak kepolisian sebelum memuat hasil wawancara itu, dengan tujuan untuk membantu pihak kepolisian dalam menemukan Jendra yang sedang buron.
Hak Tolak
Saya membayangkan seandainya keputusan si “Boss Besar” dalam sinetron itu diikuti juga di dunia nyata oleh para “Boss Besar” media cetak dan televisi yang menayangkan Dharmono K. Lawi, mantan Ketua DPRD Banten yang menjadi terpidana kasus korupsi dan berstatus buron sejak April 2006 lalu. Hal itu tentu tidak akan membuat Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh menjadi “uring-uringan” seperti sekarang ini. Hal yang membuat Jaksa Agung semakin “uring-uringan” adalah argumen dari kalangan media dan pakar hukum bahwa wartawan yang berhasil menemukan Dharmono punya hak untuk menolak mengungkapkan keberadaan Dharmono yang sedang buron itu apabila aparat penegak hukum meminta keterangan mengenai hal tersebut. Menurut mereka, hak itu diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) yang disebut sebagai Hak Tolak.
Berkenaan dengan hal itu, Jaksa Agung menyampaikan keprihatinannya terhadap wartawan yang “memburu” Dharsono hanya untuk kepentingan pemberitaan saja tapi tidak mau melaporkan keberadaan Dharsono itu kepada aparat penegak hukum. Padahal, menurut Jaksa Agung, setiap warga negara memiliki kewajiban hukum untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila mengetahui ada tindak kejahatan.
Aturan Hukum
Mengenai kewajiban hukum warga Negara berkaitan dengan keberadaan buronan itu, sebenarnya kita dapat melihat ketentuan Pasal 221 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang pada pokoknya mengatur bahwa barangsiapa yang dengan sengaja: (i) menyembunyikan pelaku kejahatan atau orang yang dituntut karena kejahatan; atau (ii) memberi pertolongan kepada pelaku kejahatan untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat yang berwenang, dapat dikenai sanksi pidana penjara maksimal sembilan bulan penjara.
Sedangkan dalam UU Pers diatur bahwa dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak, yaitu hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama dan/atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya. Hak tersebut dapat digunakan jika wartawan dimintai keterangan oleh pejabat penyidik dan/atau diminta menjadi saksi di pengadilan.
Kalau begitu, apakah seorang wartawan dapat menggunakan Hak Tolaknya untuk melindungi keberadaan seorang buronan? Menurut saya perlu dipertimbangkan latar belakang dari penggunaan Hak Tolak itu. Apabila memang buronan itu adalah sumber berita dari wartawan yang bersangkutan, maka wartawan itu dapat menggunakan Hak Tolaknya. Dengan demikian ketentuan Pasal 221 ayat (1) KUHP tidak dapat diberlakukan kepada wartawan yang menolak mengungkapkan keberadaan buronan yang menjadi sumber beritanya, karena hal itu dilindungi oleh UU Pers yang merupakan lex specialis dari KUHP.
Namun, apakah itu berarti Hak Tolak bersifat mutlak? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu melihat penjelasan mengenai Hak Tolak dalam UU Pers, yang mengatakan bahwa Hak Tolak dapat dibatalkan demi kepentingan dan keselamatan Negara atau ketertiban umum yang dinyatakan oleh pengadilan. Dengan demikian, sebenarnya Hak Tolak itu tidak bersifat mutlak.
Menimbang hal di atas, seharusnya saat ini Jaksa Agung tidak perlu patah semangat dalam mengejar buronan yang menjadi sumber berita wartawan itu, karena Jaksa Agung masih punya peluang untuk mendapatkan informasi mengenai keberadaan buronan itu. Jaksa Agung dapat meminta penetapan dari pengadilan untuk membatalkan Hak Tolak dari wartawan yang bersangkutan. Apabila setelah terbit penetapan pengadilan yang membatalkan Hak Tolaknya, wartawan yang bersangkutan masih juga menolak mengungkapkan keberadaan buronan itu, maka ketentuan Pasal 221 ayat (1) KUHP dapat dikenakan terhadap wartawan itu.