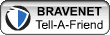Revisi Pasal 11 UUD 1945 : Mencari Mekanisme Ideal Pembuatan Perjanjian Dengan Negara Lain*by Ari Juliano Gema
Polemik mengenai pembukaan hubungan dagang dengan Israel, yang tentunya akan dibuat dalam bentuk perjanjian kerjasama ekonomi antara kedua negara, untuk sementara waktu telah usai. Pada hari Kamis tanggal 18 November 1999, Menteri Luar Negeri RI Alwi Shihab menyatakan bahwa rencana pembukaan hubungan dagang dengan Israel untuk sementara ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan.
Mengenai masalah pembuatan perjanjian kerjasama ekonomi dengan Israel ini kiranya masih menyisakan pertanyaan bagi sebagian besar masyarakat. Apakah pemerintah dapat begitu saja mengadakan atau membatalkan rencana suatu perjanjian dengan negara lain, tanpa memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat? Bagaimana peran lembaga perwakilan rakyat, dalam hal ini DPR, mengenai pembuatan perjanjian dengan negara lain?
Tulisan ini akan membahas mengenai permasalahan diatas, yang pembahasannya tidak terlepas dengan pengaturannya dalam konstitusi, yaitu pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : "Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain". Dari pasal tersebut akan dijabarkan mengenai pengertian perjanjian dengan negara lain, pembuatan perjanjian dengan negara lain, peran DPR berdasarkan UUD 1945 serta beberapa usulan sebagai solusi dari permasalahan diatas.
PERJANJIAN DENGAN NEGARA LAIN
Perjanjian dengan negara lain disini dimaksudkan sebagai perjanjian internasional yang oleh Mochtar Kusumaatmadja diartikan sebagai perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat-akibat hukum tertentu (Mochtar Kusumaatmadja, 1976:109). Sedang Oppenheim dalam bukunya International Law (A Treaties) mendefinisikannya sebagai "International treaties are states, creating legal rights and obligations between the Parties". Pada prakteknya perjanjian internasional tidak hanya dilakukan antara dua negara (bilateral) atau lebih dari dua negara (multilateral) saja, tapi juga antara satu negara dengan suatu badan atau organisasi internasional.
PEMBUATAN PERJANJIAN DENGAN NEGARA LAIN
Dilihat dari prosedurnya, lazimnya perjanjian internasional dibuat melalui tiga tahap, yaitu perundingan (negotiation), penandatanganan (signature), dan pengesahan (ratification) (Mochtar Kusumaatmadja, 1976:121). Perundingan biasanya dilakukan oleh wakil-wakil negara yang diutus oleh negara-negara peserta berdasarkan mandat tertentu. Apabila perundingan mencapai kesepakatan, maka perundingan tersebut meningkat pada tahap penandatanganan. Perjanjian yang telah ditandatangani itu, selanjutnya memerlukan pengesahan (ratification) dari negara pemberi mandat. Prosedur pengesahan (ratification) itu pada umumnya diatur di dalam konstitusi yang berlaku di tiap-tiap negara.
Prosedur pengesahan sebagai tahap terakhir dari suatu perjanjian internasional berbeda-beda antara negara yang satu dengan negara lainnya. Ada pengesahan perjanjian internasional yang cukup dilakukan oleh presiden atau kepala negara. Tetapi ada pula negara-negara yang menentukan bahwa pengesahan perjanjian internasional harus melibatkan lembaga perwakilan rakyat.
Ide mengenai keterlibatan lembaga perwakilan rakyat dalam pengesahan ini erat hubungannya dengan paham kedaulatan rakyat dan paham demokrasi yang dianut oleh tiap-tiap negara (Yusril Ihza Mahendra, 1993:124-125). Mengingat bahwa suatu perjanjian internasional, akan membawa akibat-akibat hukum tertentu, yaitu timbulnya hak dan kewajiban, serta berbagai implikasi di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan, dan sebagainya, maka sudah seharusnya perjanjian itu tidak hanya disahkan oleh pihak eksekutif, tetapi masih memerlukan persetujuan dari lembaga perwakilan rakyat sebagai perwujudan asas kedaulatan rakyat,
PERAN DPR MENURUT UUD 1945
Sebagaimana diterangkan di atas, pada pasal 11 UUD 1945 menentukan bahwa presiden dengan persetujuan DPR membuat perjanjian dengan negara lain. Pengaturan itu sendiri sebenarnya masih belum jelas dan menimbulkan beberapa penafsiran.
Pertama, tidak jelas kapan persetujuan dari DPR itu diperlukan, apakah sebelum perjanjian dengan negara lain itu dibuat, atau persetujuan itu diperlukan pada tahap-tahap tertentu dari proses pembuatan perjanjian internasional, atau persetujuan DPR hanya diperlukan pada tahap pengesahan perjanjian tersebut.
Kedua, tidak jelas dalam bentuk apa persetujuan dari DPR itu harus diberikan, apakah dalam bentuk undang-undang atau bentuk lainnya, sebab dari segi bahasa "persetujuan" tersebut tidak harus dituangkan dalam suatu bentuk yang pasti dan tetap, yang penting adalah adanya persesuaian pendapat, adanya kecocokan dalam langkah dan adanya keselarasan dalam pendirian dan penilaian (AH Saleh Attamimi,1981:292).
Ketiga, tidak jelas apakah DPR yang berinisiatif untuk memberikan persetujuan atau menunggu dimintakan persetujuannya oleh pemerintah.
Berkenaan dengan ketidakjelasan tersebut, Presiden Soekarno pernah mengirimkan surat kepada Ketua DPR (Sementara) tertanggal 22 Agustus 1960, yang mengemukakan pendirian pemerintah terhadap pasal 11 UUD 1945. Disebutkan bahwa menurut "penafsiran" pemerintah, ketentuan pasal 11 "tidak mengandung arti segala perjanjian dengan negara asing", tetapi perjanjian-perjanjian yang "terpenting saja".
Yang dimaksud dengan perjanjian "terpenting" itu menurut "penafsiran" Presiden Soekarno ialah perjanjian-perjanjian "yang mengandung soal-soal politik". Ada tiga kriteria untuk menentukan istilah perjanjian yang bersifat "terpenting", yaitu: (a) perjanjian yang membawa implikasi kepada "haluan politik luar negeri" RI seperti perjanjian persahabatan dengan negara lain, pembentukan aliansi, dan penetapan serta perubahan tapal batas negara; (b) persetujuan-persetujuan yang demikian rupa sifatnya" sehingga diperkirakan dapat "mempengaruhi haluan politik luar negeri" RI, misalnya dalam persetujuan kerjasama ekonomi, teknik, ataupun pinjaman dana dari luar negeri; (c) soal-soal yang menurut UUD atau peraturan perundang-undangan harus diatur dengan undang-undang, seperti soal-soal kewarganegaraan dan kehakiman, seperti ekstradisi.
Menurut surat Presiden Soekarno itu, perjanjian-perjanjian dengan negara lain, di luar materi dari ketiga kriteria di atas, tidak perlu dimintakan persetujuannya kepada DPR. Persetujuan perjanjian-perjanjian itu cukup dilakukan oleh presiden dan setelah itu disampaikan kepada DPR "hanya untuk diketahui". Surat ini dikemudian hari diperkuat dengan Surat Mensesneg No. 202/M.M. Sekneg/8/1975.
Walaupun telah dikemukakan penafsiran pemerintah terhadap pasal 11 UUD 1945 itu, pada prakteknya terdapat inkonsistensi dari pihak pemerintah. Berdasarkan data di lapangan pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, tercatat Trade Agreement dengan Korea Utara yang ditandatangani di Jakarta pada tahun 1964, hanya disahkan dengan Keputusan Presiden No. 91 Tahun 1964, padahal agreement tersebut telah memenuhi kriteria yang ditentukan dalam surat presiden tersebut, dalam hal ini persetujuan kerjasama ekonomi, untuk dimintakan persetujuannya kepada DPR. Kemudian Persetujuan Kerjasama bidang Ekonomi dan Kebudayaan dengan Pakistan pada tahun 1965 juga hanya disahkan dengan Keppres No. 307/1965, dan masih banyak contoh lain yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.
Akibat inkonsistensi ini dapat dikatakan bahwa surat Presiden kepada Ketua DPR tersebut telah kehilangan "kekuatannya" karena telah dilanggar sendiri oleh pembuatnya.
Dilihat dari sudut hukum tata negara, surat Presiden Soekarno, termasuk Surat Mensesneg yang keluar belakangan, itu tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Surat Presiden Soekarno itu hanya sebuah visi penafsiran pihak pemerintah terhadap pasal 11 UUD 1945, yang ditujukan kepada "Yang Mulia Ketua DPR" bukan kepada DPR sebagai sebuah lembaga tinggi negara yang kedudukannya sejajar dengan presiden (Yusril Ihza Mahendra, 1993:128).
Berdasarkan TAP MPR No. I/MPR/1983 jo. TAP MPR RI No. I/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib MPR RI pasal 4 point b disebutkan bahwa MPR mempunyai wewenang untuk memberikan penjelasan yang bersifat penafsiran terhadap putusan-putusan MPR, yang apabila dikaitkan dengan ketentuan pasal 3 TAP MPR tersebut dijelaskan bahwa MPR bertugas menetapkan Undang-Undang Dasar, sehingga sudah jelas bahwa secara ketatanegaraan yang mempunyai wewenang untuk menafsirkan UUD 1945, dalam hal ini pasal 11 UUD 1945, adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat.
PRAKTEK PADA DASAWARSA 1990-AN
Praktek pembuatan perjanjian dengan negara lain pada dasawarsa 1990-an apabila dilihat dari data di lapangan menunjukkan bahwa sejak tahun 1980 sampai dengan 1999 tercatat kurang lebih 20 (dua puluh) perjanjian internasional telah disahkan dalam bentuk undang-undang, sedangkan lebih dari 300 (tiga ratus) perjanjian internasional disahkan dengan keputusan presiden (Keppres). Apabila dibandingkan antara perjanjian internasional yang disahkan dengan undang-undang dan keputusan presiden, maka akan terlihat bahwa untuk perjanjian internasional yang bersifat bilateral biasanya disahkan dalam bentuk keputusan presiden (Keppres), sedangkan untuk perjanjian internasional yang bersifat multilateral biasanya disahkan dengan undang-undang.
Tetapi pada perkembangannya hal tersebut tidak berjalan secara konsisten, sebagai contoh International Natural Rubber Agreement yang merupakan perjanjian internasional yang bersifat multilateral hanya disahkan dengan Keputusan Presiden RI No. 94 Tahun 1996, kemudian juga ASEAN Agreement on Costums (Persetujuan ASEAN Di Bidang Kepabeanan) yang hanya disahkan dengan Keppres RI No. 130/1998. Hal ini juga terjadi pada perjanjian internasional yang bersifat bilateral, sebagai contoh Perjanjian antara RI dan Australia mengenai Zone Kerjasama di Daerah antara Propinsi Timor Timur dan Australia Bagian Utara ternyata disahkan dengan UU No. 1 Tahun 1991.
Untuk menegaskan masalah ini, Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Tahun 1999 telah mengeluarkan Ketetapan MPR RI No. IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004, yang mana pada Bab IV mengenai Arah Kebijakan bidang Hukum angka 4 ditegaskan: "Melanjutkan ratifikasi konvensi internasional, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan bangsa dalam bentuk undang-undang". Kemudian pada bidang Politik bagian Hubungan Internasional diterangkan: "Dalam melakukan perjanjian dan kerjasama internasional yang menyangkut kepentingan dan hajat hidup rakyat banyak harus dengan persetujuan lembaga perwakilan rakyat".
Merupakan perkembangan yang menggembirakan dengan keluarnya TAP MPR No. IV/MPR/1999 tersebut untuk lebih menegaskan tentang pembuatan perjanjian dengan negara lain, dan juga TAP MPR tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat dibandingkan dengan Surat Presiden No. 2826/HK/1960 kepada ketua DPRS. Namun begitu, ketentuan dalam TAP MPR tersebut apabila kita cermati ternyata juga masih mengandung beberapa penafsiran.
Pertama, mengenai bidang Hukum, tidak ada kejelasan bagaimana menentukan suatu konvensi internasional sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan bangsa sehingga dapat diratifikasi, dan siapa yang berwenang menentukan suatu konvensi internasional sudah sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan bangsa sehingga dapat diratifikasi.
Kedua, mengenai bidang Politik bagian Hubungan Internasional, tidak jelas dalam bentuk apa persetujuan lembaga perwakilan rakyat diwujudkan.
Ketiga, tidak dijelaskan pada tahap mana harus mendapat persetujuan dari lembaga perwakilan rakyat, apakah pada saat pemerintah menyatakan niatnya untuk mengadakan perjanjian atau kerjasama dengan negara lain, atau persetujuan itu diharuskan pada tahapan tertentu saja dari prosedur perjanjian internasional, misalnya pada tahap perundingan, penandatanganan, atau pengesahan saja.
Keempat, tidak dijelaskan apa kriteria dari perjanjian dan kerjasama internasional yang menyangkut kepentingan dan hajat hidup rakyat banyak.
Kelima, tidak dijelaskan apakah lembaga perwakilan rakyat harus berinisiatif untuk memberikan persetujuan, atau menunggu dimintakan persetujuannya oleh pemerintah.
Keenam, tidak dijelaskan apakah lembaga perwakilan rakyat punya hak menolak perjanjian dan kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini patut dipertanyakan karena pengertian persetujuan berbeda dengan izin yang bermakna larangan bagi yang tidak memiliki izin, sedang persetujuan hanya bersifat mengesahkan suatu perbuatan atau tindakan yang pada dasarnya tidak dilarang.
Dari paparan diatas, dapat dilihat bahwa pengaturan bagi pembuatan perjanjian dengan negara lain dalam TAP MPR No. IV/MPR/1999 masih kurang memadai sehingga akan menimbulkan kesimpangsiuran pemahaman pada pelaksanaannya nanti.
USULAN PEMECAHAN MASALAH
Melihat pada permasalahan yang dipaparkan sebelumnya, kiranya perlu dipikirkan untuk melakukan pembaharuan pada pasal 11 UUD 1945 sejalan dengan semangat pembaharuan konstitusi negara kita, agar dapat mengakomodir perkembangan maupun permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul di masa yang akan datang, sebagaimana juga lazimnya konstitusi negara lain yang secara tegas dan jelas memuat pengaturan mengenai perjanjian dan kerjasama internasional.
Adapun mengenai pembaharuan pasal 11 UUD 1945 ini perlu diperhatikan beberapa hal penting.
Pertama, harus ditegaskan bahwa untuk masuk ke dalam dan keluar dari, serta menandatangani suatu perjanjian atau kerjasama dengan negara lain atau suatu organisasi internasional, dilakukan oleh Presiden hanya dengan kuasa undang-undang. Hal ini perlu ditegaskan agar Presiden tidak berlaku sewenang-wenang untuk melakukan atau membatalkan perjanjian ataupun kerjasama internasional tanpa memperhatikan aspirasi rakyat yang disampaikan melalui lembaga perwakilannya.
Kedua, harus ditegaskan bahwa semua perjanjian dan kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah harus mendapat pengesahan dari lembaga perwakilan rakyat dalam bentuk undang-undang, kecuali jika ditentukan lain dalam undang-undang. Hal ini perlu diatur karena disadari ada perjanjian atau kerjasama internasional yang membawa akibat-akibat hukum serta menimbulkan hak dan kewajiban bagi rakyat banyak sehingga membutuhkan partisipasi rakyat melalui lembaga perwakilannya untuk mengesahkannya, dan ada juga yang materinya bersifat spesifik atau individual sehingga tidak terlalu dibutuhkan pengesahan dari lembaga perwakilan rakyat.
Ketiga, harus dibuat undang-undang organik mengenai pembuatan perjanjian dan kerjasama internasional, yang setidak-tidaknya memuat pengertian mengenai perjanjian dan kerjasama internasional, kriteria yang tegas mengenai perjanjian dan kerjasama internasional yang harus disahkan dalam bentuk undang-undang, serta hak inisiatif lembaga perwakilan rakyat untuk mengajukan RUU yang menyangkut pembuatan perjanjian dan kerjasama internasional.
KEPUSTAKAAN
Attamimi, Abdoel Hamid Saleh. (1981). "Presiden dengan Persetujuan DPR Membuat Persetujuan dengan Negara Lain". Himpunan Laporan Hasil Pengkajian Bidang Hukum Tata Negara Tahun 1980/1981-1981/1982.(Jakarta:BPHN).
Departemen Kehakiman RI. (1975). Himpunan Daftar Perjanjian Internasional. (Jakarta:Depkeh RI).
Kusumaatmadja, Mochtar. (1976). Pengantar Hukum Internasional. (Bandung:Alumni).
Lubis, M. Solly. (1997). Pembahasan UUD 1945 (Bandung:PT.Alumni).
Mahendra, Yusril Ihza. (1993). "Peranan DPR dalam Ratifikasi Perjanjian Internasional". Dinamika Tatanegara Indonesia.(Jakarta:Mizan)
Sekretariat Jenderal MPR RI. (1999). Ketetapan-Ketetapan MPR RI Hasil Sidang Umum MPR RI Tahun 1999. (Jakarta:Setneg RI).
Suryono, Edy. (1984). Praktek Ratifikasi Perjanjian Internasional di Indonesia (Bandung:Remaja Karya).
* Artikel ini ditulis pada tahun 1999, pada saat penulis bekerja sebagai staf peneliti di CSIS