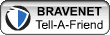Cabut Pasal 32 ayat (1) huruf (c) UU KPK!
oleh Ari Juliano Gema
Sidang pemeriksaan pendahuluan atas Permohonan Uji Materi Pasal 32 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) telah digelar pada Senin, 26 Oktober 2009 lalu. Pasal 32 ayat (1) huruf (c) UU KPK pada pokoknya mengatur bahwa pimpinan KPK diberhentikan tetap apabila menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana.
Chandra M. Hamzah dan Bibit S. Rianto mengajukan permohonan agar Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 32 ayat (1) huruf (c) UU KPK tidak berlaku karena bertentangan dengan UUD 1945, khususnya mengenai hak konstitusional warga negara untuk mendapat perlakuan yang sama dihadapan hukum. Apa alasannya?
Apabila dibandingkan dengan lembaga atau komisi negara lainnya, kedudukan pimpinan KPK sebagai pejabat negara memang sangat lemah sekali. Pemeriksaan atas dugaan tindak pidana oleh pihak kepolisian terhadap pimpinan KPK tidak memerlukan ijin dari Presiden. Bandingkan dengan perlakuan yang diterima pejabat negara lain, seperti anggota DPR, DPD atau Kepala Daerah.
Selain itu, dalam beberapa undang-undang yang mencantumkan ketentuan mengenai pemberhentian tetap seorang pimpinan lembaga atau komisi negara selain KPK, ditegaskan bahwa mereka diberhentikan tetap apabila dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal ini bisa dilihat dalam UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, UU No. 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden, atau UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
Bandingkan dengan pimpinan KPK yang dapat diberhentikan tetap hanya karena dikenakan status terdakwa. Padahal orang yang berstatus terdakwa belumlah dapat dianggap bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Bagaimana mungkin pimpinan KPK yang belum tentu bersalah harus menerima resiko kehilangan jabatannya hanya karena dikenakan status terdakwa?
Hal ini secara jelas memperlihatkan diskriminasi terhadap pimpinan KPK. Diskriminasi ini pada akhirnya melemahkan posisi pimpinan KPK. Hanya dengan menggunakan Pasal 421 KUHP mengenai penyalahgunaan wewenang yang sangat lentur penerapannya (pasal karet), aparat penegak hukum begitu mudahnya mengkriminalisasi kewenangan KPK, dengan tujuan untuk memberhentikannya.