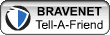Blame it on Nietzsche!
Melalui tulisan ini perkenankan saya menjelaskan mengapa saya merubah tajuk jurnal underground ini, dari “Fiat justitia ruat coelum!” menjadi “The Last Man’s Standing”.
Pada suatu hari, seorang kawan menanyakan tentang sub-title jurnal ini yang merupakan kutipan dari ucapan Prof. Charles Himawan.
“Apa itu juga filosofi hidup loe?” Tanya kawan itu.
“Bisa dibilang begitu,” jawab saya.
“Berarti loe nggak punya ambisi jadi orang kaya, dong?”
“Kalau ambisi yang loe maksud itu artinya tujuan hidup utama, jelas itu bukan ambisi gue”
“Apa loe merasa hidup loe udah cukup?” Tanya kawan itu lagi.
“Cukup itu relatif. Yang pasti gue udah merasa bahagia dengan keadaan gue sekarang ini,” jelas saya.
Kawan itu kelihatan berpikir sejenak sebelum kembali bertanya, ”are you the Last Man?”
Pertanyaan terakhir itu membuat ingatan saya mengembara kembali ke masa-masa kuliah beberapa tahun yang lalu. Saat saya masih sempat melakukan “eksperimen otak”. Ya, uji batas kemampuan otak saya dalam memahami buku-buku karangan filosof ataupun buku-buku yang membahas pemikiran filosof seperti Hegel, Karl Marx, Frederick Engels dan Friedrich Nietzsche.
Salah satu buku yang pernah saya baca adalah buku berjudul Thus Spoke Zarathustra buah karya Friedrich Nietzsche, filosof kelahiran Jerman, yang terbit pertama kali pada tahun 1883. Dari buku itu, saya mengenal tokoh Übermensch, yang dalam bahasa Inggris sering diterjemahkan sebagai the Overman. Übermensch adalah tokoh ideal ciptaan Nietzsche yang memiliki ambisi untuk berkuasa, tidak pernah puas, selalu ingin lebih dari yang lain, dan mampu menciptakan nilai-nilai untuk dirinya sendiri lepas dari nilai-nilai tradisional yang telah ada. Selain itu, ada lagi tokoh ciptaan Nietzsche yang merupakan kebalikan dari Übermensch, yaitu der letzte Mensch, yang dalam bahasa Inggris sering diterjemahkan sebagai the Last Man.
Dalam buku itu, tokoh the Last Man “dicibir” oleh Nietzsche sebagai tokoh yang lemah, tidak mau mengambil resiko, cepat puas dengan apa yang sudah dicapainya, dan hanya mencari keamanan dan kenyamanan hidup. Tokoh the Last Man muncul lagi dalam buku karya Francis Fukuyama, pengamat politik dari Amerika Serikat, yang berjudul The End of History and the Last Man, yang terbit pertama kali pada tahun 1992.
Dalam buku karya Fukuyama itu dijelaskan bahwa setelah runtuhnya negara komunis raksasa Uni Soviet di akhir tahun 1980-an, di dunia ini sudah tidak ada lagi pertarungan ideologi. Kapitalisme dengan demokrasi liberal telah mencapai kemenangannya dan menjadi satu-satunya ideologi yang dipercaya bisa membawa manusia kepada kesejajaran dalam mencapai kemakmuran. Pada saat itulah, sejarah manusia berakhir, karena tidak ada lagi pertarungan ideologi yang dapat dicatat dalam sejarah manusia. Selanjutnya, lahirlah manusia-manusia terakhir (the Last Man), yang tidak lagi peduli pada ideologi dan cenderung apatis dalam pilihan-pilihan politiknya. Oleh karena itu, pandangan terhadap partai politik juga berubah, di mana persoalan ideologi tidak lagi menjadi penting. Yang terpenting adalah upaya kongkrit apa yang bisa dilakukan oleh partai politik untuk kesejahteraan rakyat.
Pertanyaan terakhir dari kawan saya itu mungkin muncul karena dalam buku berjudul Thus Spoke Zarathustra terdapat pernyataan dari the Last Man yang mirip dengan jawaban terakhir saya, yang kurang lebih berbunyi seperti ini:
“We have invented happiness,” says the last men, and they blink.
Saya katakan kepada kawan saya, bahwa saya merasa bahagia dengan keadaan saya saat ini bukan karena saya tidak berani mengambil resiko untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik lagi. Namun, kebahagiaan saya adalah semata-mata karena rasa syukur saya kepada Tuhan Yang Maha Pengasih atas segala rizki yang telah saya dapat di dunia ini. Tapi saya katakan kepada kawan saya bahwa saya tidak peduli apabila Nietzsche, Fukuyama dan pengikut mereka “mencibir” saya sebagai the Last Man.
Bukankah lebih baik menjadi the Last Man, daripada menjadi the Overman namun kemudian segala sifat supernya itu dipakai untuk menindas dan memperbudak manusia lain, sebagaimana dilakukan Hitler, Stalin, Benito Musolini dan pemimpin fasis lainnya?
Bukankah lebih baik memilih partai politik yang memiliki aksi-aksi kongkrit, daripada memilih partai politik yang semata-mata menonjolkan kebaikan ideologinya?
Oleh karena itulah, setelah saya pertimbangan masak-masak, tajuk jurnal ini saya ganti menjadi “The Last Man’s Standing” sebagai pendirian dan tantangan terbuka saya terhadap “cibiran” Nietzsche, Fukuyama dan pengikut mereka atas pemikiran dan pendapat pribadi saya yang tertuang dalam tulisan-tulisan saya di jurnal ini.
Jadi, apabila ada orang yang bertanya mengapa saya mengganti tajuk jurnal ini, maka jawaban saya adalah: Blame it on Nietzsche!
Tabik,
Ari Juliano Gema
Pada suatu hari, seorang kawan menanyakan tentang sub-title jurnal ini yang merupakan kutipan dari ucapan Prof. Charles Himawan.
“Apa itu juga filosofi hidup loe?” Tanya kawan itu.
“Bisa dibilang begitu,” jawab saya.
“Berarti loe nggak punya ambisi jadi orang kaya, dong?”
“Kalau ambisi yang loe maksud itu artinya tujuan hidup utama, jelas itu bukan ambisi gue”
“Apa loe merasa hidup loe udah cukup?” Tanya kawan itu lagi.
“Cukup itu relatif. Yang pasti gue udah merasa bahagia dengan keadaan gue sekarang ini,” jelas saya.
Kawan itu kelihatan berpikir sejenak sebelum kembali bertanya, ”are you the Last Man?”
Pertanyaan terakhir itu membuat ingatan saya mengembara kembali ke masa-masa kuliah beberapa tahun yang lalu. Saat saya masih sempat melakukan “eksperimen otak”. Ya, uji batas kemampuan otak saya dalam memahami buku-buku karangan filosof ataupun buku-buku yang membahas pemikiran filosof seperti Hegel, Karl Marx, Frederick Engels dan Friedrich Nietzsche.
Salah satu buku yang pernah saya baca adalah buku berjudul Thus Spoke Zarathustra buah karya Friedrich Nietzsche, filosof kelahiran Jerman, yang terbit pertama kali pada tahun 1883. Dari buku itu, saya mengenal tokoh Übermensch, yang dalam bahasa Inggris sering diterjemahkan sebagai the Overman. Übermensch adalah tokoh ideal ciptaan Nietzsche yang memiliki ambisi untuk berkuasa, tidak pernah puas, selalu ingin lebih dari yang lain, dan mampu menciptakan nilai-nilai untuk dirinya sendiri lepas dari nilai-nilai tradisional yang telah ada. Selain itu, ada lagi tokoh ciptaan Nietzsche yang merupakan kebalikan dari Übermensch, yaitu der letzte Mensch, yang dalam bahasa Inggris sering diterjemahkan sebagai the Last Man.
Dalam buku itu, tokoh the Last Man “dicibir” oleh Nietzsche sebagai tokoh yang lemah, tidak mau mengambil resiko, cepat puas dengan apa yang sudah dicapainya, dan hanya mencari keamanan dan kenyamanan hidup. Tokoh the Last Man muncul lagi dalam buku karya Francis Fukuyama, pengamat politik dari Amerika Serikat, yang berjudul The End of History and the Last Man, yang terbit pertama kali pada tahun 1992.
Dalam buku karya Fukuyama itu dijelaskan bahwa setelah runtuhnya negara komunis raksasa Uni Soviet di akhir tahun 1980-an, di dunia ini sudah tidak ada lagi pertarungan ideologi. Kapitalisme dengan demokrasi liberal telah mencapai kemenangannya dan menjadi satu-satunya ideologi yang dipercaya bisa membawa manusia kepada kesejajaran dalam mencapai kemakmuran. Pada saat itulah, sejarah manusia berakhir, karena tidak ada lagi pertarungan ideologi yang dapat dicatat dalam sejarah manusia. Selanjutnya, lahirlah manusia-manusia terakhir (the Last Man), yang tidak lagi peduli pada ideologi dan cenderung apatis dalam pilihan-pilihan politiknya. Oleh karena itu, pandangan terhadap partai politik juga berubah, di mana persoalan ideologi tidak lagi menjadi penting. Yang terpenting adalah upaya kongkrit apa yang bisa dilakukan oleh partai politik untuk kesejahteraan rakyat.
Pertanyaan terakhir dari kawan saya itu mungkin muncul karena dalam buku berjudul Thus Spoke Zarathustra terdapat pernyataan dari the Last Man yang mirip dengan jawaban terakhir saya, yang kurang lebih berbunyi seperti ini:
“We have invented happiness,” says the last men, and they blink.
Saya katakan kepada kawan saya, bahwa saya merasa bahagia dengan keadaan saya saat ini bukan karena saya tidak berani mengambil resiko untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik lagi. Namun, kebahagiaan saya adalah semata-mata karena rasa syukur saya kepada Tuhan Yang Maha Pengasih atas segala rizki yang telah saya dapat di dunia ini. Tapi saya katakan kepada kawan saya bahwa saya tidak peduli apabila Nietzsche, Fukuyama dan pengikut mereka “mencibir” saya sebagai the Last Man.
Bukankah lebih baik menjadi the Last Man, daripada menjadi the Overman namun kemudian segala sifat supernya itu dipakai untuk menindas dan memperbudak manusia lain, sebagaimana dilakukan Hitler, Stalin, Benito Musolini dan pemimpin fasis lainnya?
Bukankah lebih baik memilih partai politik yang memiliki aksi-aksi kongkrit, daripada memilih partai politik yang semata-mata menonjolkan kebaikan ideologinya?
Oleh karena itulah, setelah saya pertimbangan masak-masak, tajuk jurnal ini saya ganti menjadi “The Last Man’s Standing” sebagai pendirian dan tantangan terbuka saya terhadap “cibiran” Nietzsche, Fukuyama dan pengikut mereka atas pemikiran dan pendapat pribadi saya yang tertuang dalam tulisan-tulisan saya di jurnal ini.
Jadi, apabila ada orang yang bertanya mengapa saya mengganti tajuk jurnal ini, maka jawaban saya adalah: Blame it on Nietzsche!
Tabik,
Ari Juliano Gema