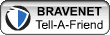Quo Vadis ‘Penggila’ Buku?*
oleh Ari Juliano Gema
Antusiasme para ‘penggila’ buku (bookaholic) pada acara “Borong Buku Murah” (BBM) yang diselenggarakan oleh Gramedia pada tanggal 26 – 28 September 2006 sangat luar biasa. Meski acara tersebut baru dibuka pada pukul 09.00 WIB, namun pengunjung sudah mulai antri dan berkerumun di gerbang Bentara Budaya Jakarta, tempat diselenggarakan acara tersebut, sejak sekitar pukul 07.00 WIB setiap harinya.
Buku-buku terbitan Kelompok Penerbit Gramedia yang dijual pada acara ini sebenarnya adalah buku-buku lama yang masih ada persediaannya di gudang atau yang sudah tidak laku dijual dengan harga normal, sehingga pihak Gramedia ‘merelakan’ buku-buku itu dijual dengan harga sangat murah, yaitu Rp 2.000,- per buku. Jenisnya pun beragam, dari novel, komik, resep masakan, sampai buku-buku non-fiksi yang bertema sosial, politik, hukum, manajemen, komputer dan psikologi. Oleh karena itulah, selama tiga hari penyelenggaraan, acara ini selalu dipenuhi ribuan pengunjung dengan perilaku ‘barbar’.
Perilaku ‘Barbar’?
Ya, begitulah kenyataannya. Bagaimana tidak ‘barbar’, ketika pertamakali pintu gerbang Bentara Budaya Jakarta dibuka, pengunjung sudah mulai saling sikut dan dorong untuk masuk ke ‘arena’.
Keadaan tidak bertambah baik ketika pengunjung sudah mulai mengerumuni buku-buku yang disusun di atas beberapa meja yang diletakkan dengan jarak yang berdekatan, sehingga menyulitkan bagi pengunjung yang ingin melintas di antara meja-meja tersebut. Buku-buku itu diperebutkan dan dilempar kesana-kemari oleh pengunjung yang berupaya memilih buku dalam suasana hiruk pikuk, berdesakan, saling sikut dan dorong itu. Bahkan ada salah seorang pengunjung yang karena sudah tidak tahan sampai akhirnya harus menginjak-injak tumpukan buku-buku itu agar bisa keluar dari kerumunan pengunjung.
Setelah puas berjibaku dalam “arena perebutan buku”, biasanya orang mulai menepi ke pinggir ‘arena’ dan mulai memilah-milah mana buku yang diambil double atau ternyata ada buku yang tidak diminatinya. Dari kegiatan ini mulai ketahuan pengunjung mana yang benar-benar ingin mengkoleksi buku, mana yang ternyata cuma berniat untuk menjual buku-buku itu kembali. Keberadaan para ‘penjual buku’ itu dengan pola “sapu bersih” yang mereka gunakan terasa sangat mengganggu ‘kenyamanan’ pengunjung yang lain. Para ‘penjual buku’ itu biasanya langsung mengambil bertumpuk-tumpuk buku dalam jumlah besar yang tersusun di atas meja tanpa melihat judul dan jenis bukunya. Hal ini jelas mengurangi kesempatan pengunjung yang lain untuk mendapatkan buku-buku yang diminatinya.
Hal yang juga disayangkan adalah adanya buku-buku yang tergeletak di lantai sebagai sisa hasil memilah-milah dari pengunjung. Buku-buku itu banyak yang terinjak-injak oleh pengunjung yang lewat sehingga kadang merusak kondisinya, padahal mungkin saja buku-buku itu masih diminati oleh pengunjung yang lain.
Harapan Kepada ‘Penggila’ Buku
Pada dasarnya, ada berbagai alasan orang untuk membeli buku, yaitu diantaranya, pertama, karena tertarik dengan sampul buku yang menarik, sehingga akan terlihat bagus kalau dipajang di rak buku. Kedua, karena sekedar ingin membuat rak buku terlihat penuh. Ketiga, karena tertarik dengan topik bukunya. Keempat, karena rekomendasi teman yang pernah membaca buku itu sebelumnya. Kelima, karena penggemar karya penulis tertentu. Keenam, karena berharap dapat dijual kembali.
Orang-orang dengan berbagai alasan itulah yang berkumpul di acara BBM itu. Semua orang dengan berbagai alasan itu bercampur baur kepentingannya dan saling bersinggungan satu sama lain. Disokong dengan harga buku yang murah dan kepentingan masing-masing individu itulah sehingga para pengunjung berubah sesaat menjadi sekelompok ‘barbarian’ yang saling ‘menjegal’ untuk mendapatkan buku yang diinginkannya.
Bagaimanapun juga, sebuah buku merupakan suatu karya yang dihasilkan dari olah pikir penulisnya. Tak ada penulis yang ingin bukunya hanya dijadikan pajangan saja. Bukan pula sekedar menjadi barang yang diberi label harga. Setiap penulis pasti ingin agar ide dan gagasan yang disampaikannya di dalam buku dapat diterima oleh pembacanya, dan mungkin juga dapat mempengaruhi pola pikir dan tingkah laku pembacanya.
oleh Ari Juliano Gema
Antusiasme para ‘penggila’ buku (bookaholic) pada acara “Borong Buku Murah” (BBM) yang diselenggarakan oleh Gramedia pada tanggal 26 – 28 September 2006 sangat luar biasa. Meski acara tersebut baru dibuka pada pukul 09.00 WIB, namun pengunjung sudah mulai antri dan berkerumun di gerbang Bentara Budaya Jakarta, tempat diselenggarakan acara tersebut, sejak sekitar pukul 07.00 WIB setiap harinya.
Buku-buku terbitan Kelompok Penerbit Gramedia yang dijual pada acara ini sebenarnya adalah buku-buku lama yang masih ada persediaannya di gudang atau yang sudah tidak laku dijual dengan harga normal, sehingga pihak Gramedia ‘merelakan’ buku-buku itu dijual dengan harga sangat murah, yaitu Rp 2.000,- per buku. Jenisnya pun beragam, dari novel, komik, resep masakan, sampai buku-buku non-fiksi yang bertema sosial, politik, hukum, manajemen, komputer dan psikologi. Oleh karena itulah, selama tiga hari penyelenggaraan, acara ini selalu dipenuhi ribuan pengunjung dengan perilaku ‘barbar’.
Perilaku ‘Barbar’?
Ya, begitulah kenyataannya. Bagaimana tidak ‘barbar’, ketika pertamakali pintu gerbang Bentara Budaya Jakarta dibuka, pengunjung sudah mulai saling sikut dan dorong untuk masuk ke ‘arena’.
Keadaan tidak bertambah baik ketika pengunjung sudah mulai mengerumuni buku-buku yang disusun di atas beberapa meja yang diletakkan dengan jarak yang berdekatan, sehingga menyulitkan bagi pengunjung yang ingin melintas di antara meja-meja tersebut. Buku-buku itu diperebutkan dan dilempar kesana-kemari oleh pengunjung yang berupaya memilih buku dalam suasana hiruk pikuk, berdesakan, saling sikut dan dorong itu. Bahkan ada salah seorang pengunjung yang karena sudah tidak tahan sampai akhirnya harus menginjak-injak tumpukan buku-buku itu agar bisa keluar dari kerumunan pengunjung.
Setelah puas berjibaku dalam “arena perebutan buku”, biasanya orang mulai menepi ke pinggir ‘arena’ dan mulai memilah-milah mana buku yang diambil double atau ternyata ada buku yang tidak diminatinya. Dari kegiatan ini mulai ketahuan pengunjung mana yang benar-benar ingin mengkoleksi buku, mana yang ternyata cuma berniat untuk menjual buku-buku itu kembali. Keberadaan para ‘penjual buku’ itu dengan pola “sapu bersih” yang mereka gunakan terasa sangat mengganggu ‘kenyamanan’ pengunjung yang lain. Para ‘penjual buku’ itu biasanya langsung mengambil bertumpuk-tumpuk buku dalam jumlah besar yang tersusun di atas meja tanpa melihat judul dan jenis bukunya. Hal ini jelas mengurangi kesempatan pengunjung yang lain untuk mendapatkan buku-buku yang diminatinya.
Hal yang juga disayangkan adalah adanya buku-buku yang tergeletak di lantai sebagai sisa hasil memilah-milah dari pengunjung. Buku-buku itu banyak yang terinjak-injak oleh pengunjung yang lewat sehingga kadang merusak kondisinya, padahal mungkin saja buku-buku itu masih diminati oleh pengunjung yang lain.
Harapan Kepada ‘Penggila’ Buku
Pada dasarnya, ada berbagai alasan orang untuk membeli buku, yaitu diantaranya, pertama, karena tertarik dengan sampul buku yang menarik, sehingga akan terlihat bagus kalau dipajang di rak buku. Kedua, karena sekedar ingin membuat rak buku terlihat penuh. Ketiga, karena tertarik dengan topik bukunya. Keempat, karena rekomendasi teman yang pernah membaca buku itu sebelumnya. Kelima, karena penggemar karya penulis tertentu. Keenam, karena berharap dapat dijual kembali.
Orang-orang dengan berbagai alasan itulah yang berkumpul di acara BBM itu. Semua orang dengan berbagai alasan itu bercampur baur kepentingannya dan saling bersinggungan satu sama lain. Disokong dengan harga buku yang murah dan kepentingan masing-masing individu itulah sehingga para pengunjung berubah sesaat menjadi sekelompok ‘barbarian’ yang saling ‘menjegal’ untuk mendapatkan buku yang diinginkannya.
Bagaimanapun juga, sebuah buku merupakan suatu karya yang dihasilkan dari olah pikir penulisnya. Tak ada penulis yang ingin bukunya hanya dijadikan pajangan saja. Bukan pula sekedar menjadi barang yang diberi label harga. Setiap penulis pasti ingin agar ide dan gagasan yang disampaikannya di dalam buku dapat diterima oleh pembacanya, dan mungkin juga dapat mempengaruhi pola pikir dan tingkah laku pembacanya.
Buku adalah pengusung peradaban, kata Barbara Tuchman (1989). Tanpa buku, sejarah diam, sastra bungkam, sains lumpuh, pemikiran macet. Buku adalah mesin perubahan, jendela dunia, ‘mercu suar’ seperti kata seorang penyair, ‘yang dipancangkan di samudera waktu’. Begitu berharganya sebuah buku, sampai-sampai Thomas Jefferson (1815) pernah berkata: “Saya tidak bisa hidup tanpa buku!”
Oleh karena itu, mudah-mudahan perilaku ‘barbar’ pengunjung acara BBM itu bukan merupakan cerminan dari masyarakat ‘penggila’ buku di Indonesia. Apabila kita secara positif melihat antusiasme pengunjung acara BBM, besar harapan kita suatu saat nanti akan muncul suatu masyarakat yang tidak hanya menjadi ‘penggila’ buku, tapi berkembang juga menjadi masyarakat ‘penggila’ ilmu yang bermanfaat. Sehingga bukan hanya mampu mengumpulkan buku saja, namun juga mampu memahami dan mengamalkan ide dan gagasan di dalam buku yang dibacanya untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan orang banyak. Semoga.
* Tulisan ini diilhami pengalaman pribadi penulis sebagai pengunjung acara “Borong Buku Murah” yang diselenggarakan oleh Gramedia pada tanggal 26 – 28 September 2006.