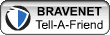Mahkamah Konstitusi yang Menjengkelkan
oleh Ari Juliano Gema
Saat ini, saya sudah tidak bisa lagi menyembunyikan kejengkelan saya terhadap Mahkamah Konstitusi (MK). Sebuah institusi yang dulu diidam-idamkan sebagai benteng penjaga nilai-nilai konstitusi, sekarang malah menjadi salah satu sumber masalah hukum terbesar di Indonesia.
Pembentukan MK
MK lahir berdasarkan amanat Perubahan Ketiga UUD 1945 pada 10 Nopember 2001. Pada Pasal 24C UUD 1945 diatur mengenai wewenang MK untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dalam rangka: (i) menguji undang-undang terhadap UUD 1945; (ii) memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; (iii) memutus pembubaran partai politik; dan (iv) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. MK juga wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945.
Kemudian, ketentuan lebih lanjut mengenai MK diatur dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK). Dalam UU MK dijelaskan lebih detil mengenai kewenangan MK berdasarkan UUD 1945 dan hukum acaranya. Pada UU MK juga dijelaskan juga bahwa undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji oleh MK adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan UUD 1945, yaitu sejak disahkannya perubahan pertama UUD 1945 pada tanggal 19 Oktober 1999.
“Dosa-Dosa” MK
Meski awalnya saya berharap banyak dengan keberadaan lembaga ini, namun ternyata mencermati perkembangan MK melalui beberapa putusannya membuat saya sangat jengkel. Bagaimana tidak jengkel, pertama, meski Pasal 50 UU MK mengatur bahwa undang-undang yang dapat diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan UUD 1945, namun MK pernah mengesampingkan ketentuan pasal itu pada saat MK menguji UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dalam putusan MK No. 004/PUU-I/2003 tanggal 30 Desember 2003. MK beralasan bahwa pengesampingan Pasal 50 UU MK bukan dalam rangka menguji pasal tersebut, melainkan hasil dari menafsirkan ketentuan Pasal 24C UUD 1945.
Terus terang, saya tidak bisa menerima kalau pengesampingan Pasal 50 UU MK itu dilakukan tanpa ada kejelasan apakah Pasal 50 UU MK itu dibatalkan atau tidak. Apabila MK mengesampingkan Pasal 50 UU MK tanpa membatalkan pasal tersebut apakah ini berarti MK juga dapat begitu saja mengesampingkan pasal-pasal yang lain dalam UU MK tanpa perlu ada mekanisme pembatalan? Untungnya, dalam putusan MK No. 066/PUU-II/2004 pada tanggal 13 April 2005 Pasal 50 UU MK itu akhirnya dibatalkan MK karena bertentangan dengan UUD 1945.
Kedua, MK seringkali memberikan putusan yang melebihi tuntutan atau petitum dari para pemohonnya (ultra petita). Sudah banyak undang-undang yang menjadi “korban” dari putusan MK yang “seenak-udelnya” ini, yaitu antara lain UU Advokat, UU Komisi Yudisial, dan yang terakhir adalah UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang telah dibatalkan secara keseluruhan. Hal ini jelas telah melanggar doktrin yang berlaku umum bahwa pengadilan hanya memutus sesuai dengan tuntutan atau petitum dari pemohonnya.
Ketiga, pada saat MK menguji UU Komisi Yudisial (KY) selain menjatuhkan putusan yang melebihi petitum, putusan MK juga menyatakan bahwa KY tidak berwenang sama sekali untuk mengawasi dan memeriksa kinerja dan perilaku hakim-hakim MK. Ada apa ini? Apakah MK ingin membangun institusi yang kebal pengawasan?
Keempat, kontroversi kembali terjadi ketika baru-baru ini MK memutuskan bahwa pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) berdasarkan Pasal 53 UU Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah bertentangan dengan UUD 1945. Masalahnya, dalam putusan itu MK masih memberikan waktu bagi Pengadilan Tipikor untuk tetap berjalan paling lama 3 tahun sampai dibentuknya UU tersendiri tentang Pengadilan Tipikor. Bagaimana mungkin sesuatu yang sudah diputus inkonstitusional namun masih diberikan waktu untuk tetap berjalan? Apakah ini berarti sifat inkonstitusional itu bisa ditangguhkan? Membingungkan sekali!
Tiada Cara Lain
Apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi “kesemrawutan” yang ditimbulkan oleh MK ini? Sayangnya tidak ada cara yang mudah. Perubahan UUD 1945 terlalu besar memberikan kekuasaan kepada MK. Ironis sekali memang. Ketika gelombang reformasi menuntut agar dibangun sistem yang menjamin agar kekuasaan lembaga-lembaga Negara dapat terkontrol dan jelas akuntabilitasnya, tiba-tiba tanpa disadari kita membesarkan sebuah lembaga yang tumbuh bagaikan makhluk rekayasa dr. Frankenstein dalam film “Frankenstein”. Ya, makhluk dengan kekuatan besar yang tidak tahu diri.
Satu-satunya cara untuk mengatasi “kesemrawutan” yang ditimbulkan oleh MK itu adalah dengan melakukan perubahan UUD 1945 sekali lagi khusus pada ketentuan mengenai MK. Hal penting yang harus diatur dalam perubahan itu adalah: (i) harus ditegaskan bahwa putusan MK tidak boleh diberikan melebihi tuntutan atau petitum dari pemohonnya; dan (ii) hakim-hakim MK adalah termasuk dalam obyek pengawasan KY.
Saat ini, saya sudah tidak bisa lagi menyembunyikan kejengkelan saya terhadap Mahkamah Konstitusi (MK). Sebuah institusi yang dulu diidam-idamkan sebagai benteng penjaga nilai-nilai konstitusi, sekarang malah menjadi salah satu sumber masalah hukum terbesar di Indonesia.
Pembentukan MK
MK lahir berdasarkan amanat Perubahan Ketiga UUD 1945 pada 10 Nopember 2001. Pada Pasal 24C UUD 1945 diatur mengenai wewenang MK untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dalam rangka: (i) menguji undang-undang terhadap UUD 1945; (ii) memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; (iii) memutus pembubaran partai politik; dan (iv) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. MK juga wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945.
Kemudian, ketentuan lebih lanjut mengenai MK diatur dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK). Dalam UU MK dijelaskan lebih detil mengenai kewenangan MK berdasarkan UUD 1945 dan hukum acaranya. Pada UU MK juga dijelaskan juga bahwa undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji oleh MK adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan UUD 1945, yaitu sejak disahkannya perubahan pertama UUD 1945 pada tanggal 19 Oktober 1999.
“Dosa-Dosa” MK
Meski awalnya saya berharap banyak dengan keberadaan lembaga ini, namun ternyata mencermati perkembangan MK melalui beberapa putusannya membuat saya sangat jengkel. Bagaimana tidak jengkel, pertama, meski Pasal 50 UU MK mengatur bahwa undang-undang yang dapat diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan UUD 1945, namun MK pernah mengesampingkan ketentuan pasal itu pada saat MK menguji UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dalam putusan MK No. 004/PUU-I/2003 tanggal 30 Desember 2003. MK beralasan bahwa pengesampingan Pasal 50 UU MK bukan dalam rangka menguji pasal tersebut, melainkan hasil dari menafsirkan ketentuan Pasal 24C UUD 1945.
Terus terang, saya tidak bisa menerima kalau pengesampingan Pasal 50 UU MK itu dilakukan tanpa ada kejelasan apakah Pasal 50 UU MK itu dibatalkan atau tidak. Apabila MK mengesampingkan Pasal 50 UU MK tanpa membatalkan pasal tersebut apakah ini berarti MK juga dapat begitu saja mengesampingkan pasal-pasal yang lain dalam UU MK tanpa perlu ada mekanisme pembatalan? Untungnya, dalam putusan MK No. 066/PUU-II/2004 pada tanggal 13 April 2005 Pasal 50 UU MK itu akhirnya dibatalkan MK karena bertentangan dengan UUD 1945.
Kedua, MK seringkali memberikan putusan yang melebihi tuntutan atau petitum dari para pemohonnya (ultra petita). Sudah banyak undang-undang yang menjadi “korban” dari putusan MK yang “seenak-udelnya” ini, yaitu antara lain UU Advokat, UU Komisi Yudisial, dan yang terakhir adalah UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang telah dibatalkan secara keseluruhan. Hal ini jelas telah melanggar doktrin yang berlaku umum bahwa pengadilan hanya memutus sesuai dengan tuntutan atau petitum dari pemohonnya.
Ketiga, pada saat MK menguji UU Komisi Yudisial (KY) selain menjatuhkan putusan yang melebihi petitum, putusan MK juga menyatakan bahwa KY tidak berwenang sama sekali untuk mengawasi dan memeriksa kinerja dan perilaku hakim-hakim MK. Ada apa ini? Apakah MK ingin membangun institusi yang kebal pengawasan?
Keempat, kontroversi kembali terjadi ketika baru-baru ini MK memutuskan bahwa pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) berdasarkan Pasal 53 UU Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah bertentangan dengan UUD 1945. Masalahnya, dalam putusan itu MK masih memberikan waktu bagi Pengadilan Tipikor untuk tetap berjalan paling lama 3 tahun sampai dibentuknya UU tersendiri tentang Pengadilan Tipikor. Bagaimana mungkin sesuatu yang sudah diputus inkonstitusional namun masih diberikan waktu untuk tetap berjalan? Apakah ini berarti sifat inkonstitusional itu bisa ditangguhkan? Membingungkan sekali!
Tiada Cara Lain
Apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi “kesemrawutan” yang ditimbulkan oleh MK ini? Sayangnya tidak ada cara yang mudah. Perubahan UUD 1945 terlalu besar memberikan kekuasaan kepada MK. Ironis sekali memang. Ketika gelombang reformasi menuntut agar dibangun sistem yang menjamin agar kekuasaan lembaga-lembaga Negara dapat terkontrol dan jelas akuntabilitasnya, tiba-tiba tanpa disadari kita membesarkan sebuah lembaga yang tumbuh bagaikan makhluk rekayasa dr. Frankenstein dalam film “Frankenstein”. Ya, makhluk dengan kekuatan besar yang tidak tahu diri.
Satu-satunya cara untuk mengatasi “kesemrawutan” yang ditimbulkan oleh MK itu adalah dengan melakukan perubahan UUD 1945 sekali lagi khusus pada ketentuan mengenai MK. Hal penting yang harus diatur dalam perubahan itu adalah: (i) harus ditegaskan bahwa putusan MK tidak boleh diberikan melebihi tuntutan atau petitum dari pemohonnya; dan (ii) hakim-hakim MK adalah termasuk dalam obyek pengawasan KY.
Apabila memang dirasakan keberadaan MK ini lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya, mungkin para anggota MPR dapat mempertimbangkan untuk membubarkan saja keberadaan MK. Bagaimanapun juga pernah ada pemikiran yang mengemuka pada saat perdebatan mengenai pembentukan MK, yaitu bahwa undang-undang merupakan produk dari kedaulatan rakyat yang dipegang dan dijalankan oleh pemerintah dan DPR, selaku pembentuk undang-undang berdasarkan asas kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, undang-undang tidak bisa dibatalkan oleh putusan satu majelis hakim yang terdiri dari beberapa orang yang tidak pernah mendapatkan mandat dari rakyat.