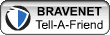Haruskah Menegakkan Hak Pemilih dengan Menerabas Konstitusi?
oleh Ari Juliano Gema
Pada dasarnya, saya turut senang dengan dibukanya peluang bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk tetap dapat menggunakan hak memilih pada Pemilihan Presiden tanggal 8 Juli lalu. Hanya dengan menunjukkan KTP dan Kartu Keluarga, pemilih non-DPT dapat memilih di TPS yang sesuai dengan alamat pada KTP-nya. Namun, terus terang saya kecewa dengan cara yang diambil untuk menegakkan hak pemilih tersebut.
MK Melanggar Konstitusi?
Pada 6 Juli lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian tuntutan dari Refly Harun dan Maheswara Prabandono yang menjadi pemohon pembatalan Pasal 28 dan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres) berkaitan dengan syarat bahwa hanya pemilih terdaftar di DPT yang dapat menggunakan hak memilihnya. Oleh para pemohon hal itu dianggap menghambat hak memilih warga negara yang merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi.
Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa Pasal 28 dan Pasal 111 UU Pilpres adalah konstitusional sepanjang diartikan mencakup warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT dengan syarat dan cara yang telah ditentukan oleh MK dalam putusan tersebut. Salah satu syarat tersebut antara lain bahwa Warga Negara Indonesia yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atau Paspor yang masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri.
Apabila membaca putusan MK tersebut secara seksama, maka kita akan melihat beberapa hal yang sepertinya tidak sesuai dengan ketentuan dalam UUD 1945, yaitu, pertama, MK mengatur syarat dan cara yang begitu rinci agar pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dapat tetap menggunakan hak pilihnya. Padahal, menurut Pasal 24C UUD 1945, salah satu wewenang MK adalah sebatas menguji undang-undang (UU) terhadap UUD 1945. Menurut UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK sendiri, MK berwenang untuk menyatakan bahwa suatu muatan materi ayat, pasal dan/atau bagian UU bertentangan atau tidak dengan UUD 1945, namun tidak ada kewenangan MK untuk membuat pengaturan lebih lanjut dari suatu UU.
Kedua, MK memandang bahwa penggunaan KTP atau Paspor yang masih berlaku untuk memilih tersebut tidak dapat diberlakukan melalui keputusan atau peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Padahal, menurut Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, yaitu KPU. Menurut UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, KPU berwenang menetapkan keputusan dan Peraturan KPU yang merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, serta menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Lagipula, MK tidak berwenang untuk menentukan apakah suatu peraturan dibawah UU dapat atau tidak dapat diberlakukan. Menurut Pasal 24A ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Agung yang memiliki wewenang untuk menguji apakah suatu keputusan atau Peraturan KPU tidak dapat diberlakukan karena bertentangan dengan UU diatasnya, dan bukan MK.
Ketiga, MK menyatakan bahwa putusan tersebut bersifat self executing, sehingga langsung dapat diterapkan oleh KPU tanpa memerlukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) guna melindungi, menjamin, dan memenuhi hak konstitusional warga negara untuk menggunakan hak pilihnya. Padahal, menurut Pasal 28I ayat (5) UUD 1945, untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia (HAM) sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan HAM, termasuk hak memilih, dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.
Menurut UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (UU No. 10/2004), jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan secara berturut-turut adalah UUD 1945, UU/Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah. Jenis peraturan lain seperti Peraturan KPU juga diakui sepanjang diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi. Dengan demikian, menurut UU No. 10/2004, Putusan MK bukanlah suatu jenis peraturan perundang-undangan, sehingga tidak dapat langsung diterapkan oleh KPU tanpa adanya UU/ Perpu yang memerintahkannya.
Ahli Hukum Bungkam atau Dibungkam?
Yang mengherankan adalah tidak terdengar komentar dari para ahli hukum berkaitan dengan substansi dari putusan MK yang meragukan tersebut, di media cetak maupun elektronik, ketika putusan MK tersebut keluar. Entah karena para ahli hukum itu takut dianggap menghalangi hak pemilih atau karena memang media massa tidak memberikan ruang atau kesempatan kepada para ahli hukum untuk mengkritisi putusan MK tersebut. Sebagian besar media massa yang berpengaruh hanya menayangkan pernyataan dari ketua MK, Mahfud MD, yang menegaskan kembali bahwa putusan MK tersebut dapat langsung dilaksanakan tanpa perlu menunggu Perpu atau peraturan KPU.
Sebenarnya, setelah putusan MK tersebut keluar pada 6 Juli lalu, Indonesian Society for Civilized Election (ISCEL), sebuah lembaga pemantau pemilu, langsung mengeluarkan siaran pers untuk mendesak KPU agar membuat Peraturan KPU yang mengatur mengenai penggunaan KTP/Passpor bagi pemilih non-DPT tersebut. Siaran pers juga menegaskan posisi ISCEL yang tidak sependapat dengan sifat self executing dari putusan MKU tersebut. Bagi ISCEL, tanpa adanya Peraturan KPU yang mengatur syarat dan cara memilih dengan menggunakan KTP/Passpor sebagaimana dimaksud putusan MK tersebut, berarti tidak ada dasar hukum yang memperbolehkan pemilih non-DPT menggunakan hak pilihnya hanya dengan menunjukkan KTP/Passpornya saja.
Namun, tidak ada satupun media massa yang memuat siaran pers tersebut. Seolah-olah semua mengamini saja putusan MK yang substansinya meragukan tersebut. Seolah-olah semua pihak membiarkan saja terjadinya proses pembodohan publik secara sistematik dengan dengan dalih demi kepentingan publik. Apalagi kemudian KPU menerbitkan surat edaran berisi petunjuk teknis yang terang-terangan merujuk pada putusan MK tersebut, seolah-olah putusan MK adalah suatu peraturan perundang-undangan diatasnya. Dengan demikian, hal ini semakin memperkuat pendapat publik yang menganggap Pemilu 2009 sebagai pemilu paling amburadul dalam sejarah penyelenggaraan pemilu di Republik Indonesia.
Labels: konstitusi, KPU, ktp, Mahkamah Konstitusi, pemilih, pemilu