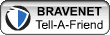Majalah Playboy, Julie Estelle dan Perlindungan Anak
oleh Ari Juliano Gema
Sidang kasus dugaan pelanggaran kesopanan yang dilakukan oleh pengelola Majalah Playboy Indonesia yang digelar di PN Jakarta Selatan beberapa waktu lalu cukup menarik perhatian saya. Bukan soal perdebatan mengenai apakah sajian dari majalah itu melanggar kesopanan yang menarik perhatian saya, tapi karena saya baru tahu bahwa Majalah Playboy Indonesia ternyata pernah menggunakan anak-anak sebagai model untuk berpose sensual pada salah satu terbitan majalah tersebut.
Tidak percaya? Silakan lihat Majalah Playboy Indonesia edisi ketiga yang terbit pada bulan Juli 2006. Salah satu model bernama Julie Estelle yang ditampilkan pada edisi tersebut ternyata baru berusia 17 tahun!
Julie Estelle Masih Anak-anak?
Kalau tidak percaya, coba buka Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak). Menurut undang-undang itu, yang dimaksud dengan “anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Jadi, apa salah kalau saya bilang Julie Estelle masih anak-anak pada saat ia menjadi model di Majalah Playboy Indonesia?
Ini serius! Bahkan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer), Julie Estelle, yang lahir pada tanggal 4 Januari 1989 itu, sebenarnya belum cukup dewasa untuk mewakili dirinya sendiri dalam membuat perikatan dengan manajemen Majalah Playboy Indonesia berkenaan dengan status dirinya sebagai seorang Playmate (sebutan bagi model Majalah Playboy). Dewasa menurut KUHper adalah apabila seseorang telah mencapai usia 21 tahun atau telah menikah.
Kedewasaan adalah syarat agar seseorang dianggap cakap/mampu untuk membuat suatu perikatan, yang mana hal itu merupakan salah satu syarat sahnya suatu perjanjian menurut KUHPer. Dengan begitu, Julie seharusnya diwakili wali/orang tuanya untuk menandatangani perjanjian apapun berkenaan dengan penampilan dia di Majalah Playboy Indonesia.
Sidang kasus dugaan pelanggaran kesopanan yang dilakukan oleh pengelola Majalah Playboy Indonesia yang digelar di PN Jakarta Selatan beberapa waktu lalu cukup menarik perhatian saya. Bukan soal perdebatan mengenai apakah sajian dari majalah itu melanggar kesopanan yang menarik perhatian saya, tapi karena saya baru tahu bahwa Majalah Playboy Indonesia ternyata pernah menggunakan anak-anak sebagai model untuk berpose sensual pada salah satu terbitan majalah tersebut.
Tidak percaya? Silakan lihat Majalah Playboy Indonesia edisi ketiga yang terbit pada bulan Juli 2006. Salah satu model bernama Julie Estelle yang ditampilkan pada edisi tersebut ternyata baru berusia 17 tahun!
Julie Estelle Masih Anak-anak?
Kalau tidak percaya, coba buka Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak). Menurut undang-undang itu, yang dimaksud dengan “anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Jadi, apa salah kalau saya bilang Julie Estelle masih anak-anak pada saat ia menjadi model di Majalah Playboy Indonesia?
Ini serius! Bahkan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer), Julie Estelle, yang lahir pada tanggal 4 Januari 1989 itu, sebenarnya belum cukup dewasa untuk mewakili dirinya sendiri dalam membuat perikatan dengan manajemen Majalah Playboy Indonesia berkenaan dengan status dirinya sebagai seorang Playmate (sebutan bagi model Majalah Playboy). Dewasa menurut KUHper adalah apabila seseorang telah mencapai usia 21 tahun atau telah menikah.
Kedewasaan adalah syarat agar seseorang dianggap cakap/mampu untuk membuat suatu perikatan, yang mana hal itu merupakan salah satu syarat sahnya suatu perjanjian menurut KUHPer. Dengan begitu, Julie seharusnya diwakili wali/orang tuanya untuk menandatangani perjanjian apapun berkenaan dengan penampilan dia di Majalah Playboy Indonesia.
Saya yakin, Playboy Enterprise Inc. sebagai penerbit dan pemilik lisensi Majalah Playboy pasti tidak mengijinkan ada seorang Playmate yang berusia di bawah 18 tahun, karena di Amerika Serikat sendiri seseorang dianggap dewasa secara hukum apabila ia telah berusia 18 tahun. Pernah ada seorang Playmate bernama Elizabeth Ann Roberts yang sebenarnya masih berusia 16 tahun ketika fotonya akan ditampilkan pada Majalah Playboy edisi Januari 1958. Namun, ibu dari Elizabeth Ann Roberts, yang mengantarkan sendiri anaknya untuk pemotretan di majalah itu, meyakinkan pihak manajemen Majalah Playboy bahwa anaknya telah berusia 18 tahun.
Walhasil, ketika Majalah Playboy yang memuat foto sensual Elizabeth Ann Roberts itu terbit, Hugh Hefner sebagai pemilik Majalah Playboy dan ibu dari Elizabeth Ann Roberts itu dituntut pidana penjara oleh pihak yang berwenang di Chicago dengan tuduhan kejahatan terhadap anak-anak. Namun, tuntutan tersebut kemudian dibatalkan karena terbukti Hugh Hefner tidak mengetahui usia Elizabeth Ann Roberts yang sebenarnya.
Saya koq jadi ngeri, ya, membayangkan kalau ada orang tua yang mau mengantar anaknya untuk difoto dengan gaya sensual agar dapat ditampilkan dalam majalah untuk orang dewasa. It doesn’t make sense!
Dimana Peran Negara?
Sejujurnya, saya prihatin dan cemas, sekaligus geram, melihat media hiburan yang begitu bebas mengeksploitasi anak-anak sampai pada batas-batas perilaku yang tidak wajar. Selain kasus Julie Estelle tadi, di beberapa sinetron tentang kehidupan remaja, seringkali anak-anak perempuannya ditampilkan memakai seragam sekolah yang ketat sehingga menonjolkan lekuk tubuhnya, dengan rok yang super mini.
Belum lagi, di film Indonesia yang menyasar kaum remaja, dengan alasan “tuntutan skenario”, pemain film yang belum dewasa “dipaksa” berciuman dengan lawan jenisnya. What the hell is it? Apakah media hiburan di Indonesia mau ditujukan untuk konsumsi kaum phaedofilia?
Seharusnya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang dibentuk atas amanat UU Perlindungan Anak lebih proaktif dalam menanggulangi fenomena eksploitasi anak-anak secara terselubung seperti itu. KPAI harus secara aktif melakukan pengawasan dan turut mendesak aparat penegak hukum agar mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara seksual terhadap anak-anak, baik yang dilakukan secara terbuka maupun terselubung. Dalam UU Perlindungan Anak telah jelas diatur bahwa setiap orang yang mengeksploitasi seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dapat dipidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda maksimal Rp 200 juta.
Mungkin anak-anak itu sendiri tidak menyadari dirinya mengalami eksploitasi secara seksual, karena dengan janji-janji ketenaran dan kelimpahan materi di dunia entertainment, mereka pasti akan mendadak “buta dan tuli” dengan eksploitasi yang menimpa dirinya. Oleh karena itu, kitalah yang masih waras ini wajib terus menerus mengingatkan dan mendesak KPAI, pemerintah dan lembaga-lembaga yang berwenang lainnya agar memperhatikan dan bertindak tegas terhadap segala bentuk eksploitasi secara seksual terhadap anak-anak.
Pokoknya, stop segala bentuk eksploitasi secara seksual terhadap anak-anak!