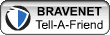Naomi Campbell, Sanksi Pidana dan Lembaga Pidana Bersyarat
oleh Ari Juliano Gema
Pada hari Senin, 19 Maret 2007, lalu, Naomi Campbell dengan sepatu hak lancipnya datang ke tempat penampungan sampah di kawasan Manhattan, New York, untuk mulai menjalani hukuman selama lima harinya, yaitu mengepel lantai dan membersihkan toilet (Antara, 20/03/07). Hukuman yang dijatuhkan pada model berusia 36 tahun itu berawal dari pengakuannya di pengadilan pada Januari 2007 lalu di mana ia mengaku bersalah secara gegabah melempar pembantu rumah tangganya dengan handphone hanya karena ia kesal pada sepasang pakaian "jeans" yang disiapkan pembantunya itu.
Dia juga didenda USD 363 sebagai ganti rugi biaya perawatan pembantunya itu dan diharuskan mengikuti pertemuan tentang mengelola kemarahan. Selama menjalani hukumannya, Naomi akan bekerja selama lima hari sejak pukul 08.00 pagi, dan setiap harinya ia bekerja selama tujuh jam dengan dua kali istirahat. Naomi adalah pesohor kedua yang baru-baru ini dijatuhi hukuman pelayanan masyarakat di New York, setelah sebelumnya penyanyi Boy George diperintahkan menyapu jalanan selama lima hari sebagai hukuman atas kepemilikan obat-obatan terlarang dan memberi laporan palsu tentang pembobolan rumahnya.
Sanksi Pidana
Ketika pertama kali membaca berita tentang kasus Naomi Campbell itu, saya jadi senyum-senyum sendiri membayangkan seandainya saja seleb-seleb kita yang sering bikin ulah itu juga dikenakan hukuman pelayanan masyarakat seperti yang dikenakan kepada Naomi Campbel dan Boy George itu. Namun, apakah sistem hukum kita memungkinkan hal itu?
Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sanksi pidana pada pokoknya terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Sebenarnya, orang yang dijatuhi pidana penjara atau pidana kurungan bisa diwajibkan bekerja di dalam atau di luar tahanannya. Namun, tidak jelas apakah definisi bekerja itu meliputi juga hukuman pelayanan masyarakat seperti yang dikenakan kepada Naomi Campbell itu. Lagipula, KUHP mengatur bahwa orang itu tetap harus ditahan terlebih dahulu.
Namun, KUHP juga mengatur bahwa apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan, maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan bahwa sanksi pidana itu tidak perlu dijalankan, dengan memberikan masa percobaan kepada orang yang bersangkutan. Apabila dalam masa percobaan itu, si terpidana melakukan suatu tindak pidana atau si terpidana tidak memenuhi suatu syarat khusus yang diperintahkan dalam putusan hakim, maka si terpidana wajib menjalani pidana penjara atau pidana kurungan yang telah diputuskan hakim tersebut. Hal ini disebut sebagai pidana bersyarat.
Lembaga Pidana Bersyarat
Menurut KUHP, disamping selama masa percobaan si terpidana tidak boleh melakukan suatu tindak pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa selama masa percobaannya si terpidana harus mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan pidananya. Disamping itu, dapat pula ditentukan syarat khusus lainnya mengenai tingkah laku si terpidana yang harus dipenuhi sepanjang atau sebagian dari masa percobaannya. Namun, syarat-syarat itu tidak boleh mengurangi kemerdekaan agama atau kemerdekaan politik dari si terpidana.
Jadi, sebenarnya sistem hukum kita memungkinkan hakim untuk memutuskan pidana bersyarat bagi seseorang dengan syarat khusus melakukan pelayanan masyarakat untuk suatu waktu tertentu selama masa percobaan. Namun, sependek pengetahuan saya sepertinya belum ada hakim yang memberikan putusan seperti itu.
Menurut penelitian Prof. Muladi, sebenarnya penerapan pidana bersyarat mengandung beberapa keuntungan. Beberapa keuntungan itu antara lain: (i) memberikan kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki dirinya di dalam masyarakat; (ii) memberikan kesempatan kepada terpidana untuk berpartisipasi dalam pekerjaan-pekerjaan, yang secara ekonomis menguntungkan masyarakat dan keluarga; dan (iii) biaya yang harus ditanggung Negara lebih murah dibandingkan dengan pidana penjara atau pidana kurungan (Muladi, 1985).
Prof. Muladi mengemukakan bahwa dalam prakteknya lembaga pidana bersyarat ini tidak dapat diterapkan secara optimal karena beberapa alasan, yaitu antara lain, pertama, belum adanya pedoman yang jelas tentang penerapan pidana bersyarat, yang mencakup hakekat, tujuan yang hendak dicapai serta ukuran-ukuran di dalam penjatuhan pidana bersyarat. Kedua, belum melembaganya pola-pola pengawasan dan pembinaan dan sistem kerjasama dalam pengawasan dan pembinaan terhadap terpidana yang dijatuhi pidana bersyarat.
Ketiga, jaksa dan hakim masih sangat selektif dan membatasi diri dalam menuntut dan menjatuhkan sanksi pidana bersyarat. Padahal sebenarnya KUHP memberikan kemungkinan untuk menerapkan sanksi pidana bersyarat secara lebih luas.
Seandainya saja semua pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan yang diputuskan hakim dapat diterapkan sanksi pidana bersyarat dengan salah satu syarat khususnya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti yang diterapkan kepada Naomi Campbell dan Boy George, maka selain memberikan efek jera pasti juga memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Apalagi apabila terpidana tersebut dapat diperbantukan untuk membantu meringankan penderitaan korban bencana alam yang kerap terjadi di tanah air dan membangun fasilitas sosial dan fasilitas umum di berbagai daerah.
Pada hari Senin, 19 Maret 2007, lalu, Naomi Campbell dengan sepatu hak lancipnya datang ke tempat penampungan sampah di kawasan Manhattan, New York, untuk mulai menjalani hukuman selama lima harinya, yaitu mengepel lantai dan membersihkan toilet (Antara, 20/03/07). Hukuman yang dijatuhkan pada model berusia 36 tahun itu berawal dari pengakuannya di pengadilan pada Januari 2007 lalu di mana ia mengaku bersalah secara gegabah melempar pembantu rumah tangganya dengan handphone hanya karena ia kesal pada sepasang pakaian "jeans" yang disiapkan pembantunya itu.
Dia juga didenda USD 363 sebagai ganti rugi biaya perawatan pembantunya itu dan diharuskan mengikuti pertemuan tentang mengelola kemarahan. Selama menjalani hukumannya, Naomi akan bekerja selama lima hari sejak pukul 08.00 pagi, dan setiap harinya ia bekerja selama tujuh jam dengan dua kali istirahat. Naomi adalah pesohor kedua yang baru-baru ini dijatuhi hukuman pelayanan masyarakat di New York, setelah sebelumnya penyanyi Boy George diperintahkan menyapu jalanan selama lima hari sebagai hukuman atas kepemilikan obat-obatan terlarang dan memberi laporan palsu tentang pembobolan rumahnya.
Sanksi Pidana
Ketika pertama kali membaca berita tentang kasus Naomi Campbell itu, saya jadi senyum-senyum sendiri membayangkan seandainya saja seleb-seleb kita yang sering bikin ulah itu juga dikenakan hukuman pelayanan masyarakat seperti yang dikenakan kepada Naomi Campbel dan Boy George itu. Namun, apakah sistem hukum kita memungkinkan hal itu?
Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sanksi pidana pada pokoknya terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Sebenarnya, orang yang dijatuhi pidana penjara atau pidana kurungan bisa diwajibkan bekerja di dalam atau di luar tahanannya. Namun, tidak jelas apakah definisi bekerja itu meliputi juga hukuman pelayanan masyarakat seperti yang dikenakan kepada Naomi Campbell itu. Lagipula, KUHP mengatur bahwa orang itu tetap harus ditahan terlebih dahulu.
Namun, KUHP juga mengatur bahwa apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan, maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan bahwa sanksi pidana itu tidak perlu dijalankan, dengan memberikan masa percobaan kepada orang yang bersangkutan. Apabila dalam masa percobaan itu, si terpidana melakukan suatu tindak pidana atau si terpidana tidak memenuhi suatu syarat khusus yang diperintahkan dalam putusan hakim, maka si terpidana wajib menjalani pidana penjara atau pidana kurungan yang telah diputuskan hakim tersebut. Hal ini disebut sebagai pidana bersyarat.
Lembaga Pidana Bersyarat
Menurut KUHP, disamping selama masa percobaan si terpidana tidak boleh melakukan suatu tindak pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa selama masa percobaannya si terpidana harus mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan pidananya. Disamping itu, dapat pula ditentukan syarat khusus lainnya mengenai tingkah laku si terpidana yang harus dipenuhi sepanjang atau sebagian dari masa percobaannya. Namun, syarat-syarat itu tidak boleh mengurangi kemerdekaan agama atau kemerdekaan politik dari si terpidana.
Jadi, sebenarnya sistem hukum kita memungkinkan hakim untuk memutuskan pidana bersyarat bagi seseorang dengan syarat khusus melakukan pelayanan masyarakat untuk suatu waktu tertentu selama masa percobaan. Namun, sependek pengetahuan saya sepertinya belum ada hakim yang memberikan putusan seperti itu.
Menurut penelitian Prof. Muladi, sebenarnya penerapan pidana bersyarat mengandung beberapa keuntungan. Beberapa keuntungan itu antara lain: (i) memberikan kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki dirinya di dalam masyarakat; (ii) memberikan kesempatan kepada terpidana untuk berpartisipasi dalam pekerjaan-pekerjaan, yang secara ekonomis menguntungkan masyarakat dan keluarga; dan (iii) biaya yang harus ditanggung Negara lebih murah dibandingkan dengan pidana penjara atau pidana kurungan (Muladi, 1985).
Prof. Muladi mengemukakan bahwa dalam prakteknya lembaga pidana bersyarat ini tidak dapat diterapkan secara optimal karena beberapa alasan, yaitu antara lain, pertama, belum adanya pedoman yang jelas tentang penerapan pidana bersyarat, yang mencakup hakekat, tujuan yang hendak dicapai serta ukuran-ukuran di dalam penjatuhan pidana bersyarat. Kedua, belum melembaganya pola-pola pengawasan dan pembinaan dan sistem kerjasama dalam pengawasan dan pembinaan terhadap terpidana yang dijatuhi pidana bersyarat.
Ketiga, jaksa dan hakim masih sangat selektif dan membatasi diri dalam menuntut dan menjatuhkan sanksi pidana bersyarat. Padahal sebenarnya KUHP memberikan kemungkinan untuk menerapkan sanksi pidana bersyarat secara lebih luas.
Seandainya saja semua pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan yang diputuskan hakim dapat diterapkan sanksi pidana bersyarat dengan salah satu syarat khususnya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti yang diterapkan kepada Naomi Campbell dan Boy George, maka selain memberikan efek jera pasti juga memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Apalagi apabila terpidana tersebut dapat diperbantukan untuk membantu meringankan penderitaan korban bencana alam yang kerap terjadi di tanah air dan membangun fasilitas sosial dan fasilitas umum di berbagai daerah.
Bagaimana menurut anda?