Perlukah Kebijakan Afirmatif dalam Menetapkan Caleg Terpilih?
oleh Ari Juliano Gema
Pemilu sudah tinggal beberapa minggu lagi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih disibukkan dengan berbagai persiapan menjelang pemilu. Salah satunya adalah mempersiapkan peraturan dalam rangka menetapkan calon anggota legislatif (caleg) terpilih. Hal ini adalah sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 22-24/PUU-VI/2008, yang membuat Pasal 214 Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (UU Pemilu) menjadi tidak berlaku.
Pasal 214 tersebut pada dasarnya mengatur bahwa calon anggota DPR/DPRD terpilih ditetapkan dengan mempertimbangkan nomor urut dalam daftar calon tetap (DCT). Sehingga bagi caleg yang memiliki nomor urut paling kecil memiliki peluang besar untuk terpilih sebagai anggota legislatif dari partainya. Namun, dengan terbitnya putusan MK tersebut, yang mana MK memberikan pertimbangan bahwa penetapan anggota DPR/DPRD terpilih seharusnya berdasarkan pada perolehan suara terbanyak, maka penetapan caleg terpilih dengan mempertimbangkan nomor urut menjadi tidak berlaku lagi.
Kebijakan Afirmatif
Sebelum putusan MK tersebut terbit, UU Pemilu telah mengakomodir kebijakan afirmatif, yaitu memberikan aturan khusus dalam rangka mendorong partisipasi perempuan agar memiliki keterwakilan yang memadai dalam lembaga legislatif. Hal ini bisa terlihat dalam beberapa ketentuan UU Pemilu, yaitu antara lain: (i) mensyaratkan partai politik menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan di tingkat pusat agar dapat menjadi peserta pemilu; (ii) mensyaratkan partai politik mengajukan daftar bakal caleg yang memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan; dan (iii) nama-nama caleg dalam daftar bakal caleg tersebut disusun berdasarkan nomor urut dimana setiap 3 orang bakal caleg terdapat sekurang-kurangnya 1 orang bakal caleg perempuan.
Dengan begitu, apabila Pasal 214 UU Pemilu masih berlaku, banyak pihak menganggap bahwa caleg perempuan yang masuk dalam “tiga besar” nomor urut terkecil DCT punya peluang besar untuk terpilih sebagai anggota legislatif. Peluang ini menjadi tidak ada dengan terbitnya putusan MK tersebut. Bagi sebagian kalangan, dengan terbitnya putusan MK tersebut kebijakan afirmatif menjadi tidak ada artinya lagi.
Menanggapi hal itu, KPU bermaksud membuat peraturan mengenai penetapan caleg terpilih dengan tetap mengakomodir kebijakan afirmatif tersebut. Apabila kebijakan afirmatif diakomodir, maka jika ada satu partai politik meraih tiga kursi di suatu daerah pemilihan, kursi ketiga akan diserahkan kepada caleg perempuan.
Tetap Suara Terbanyak
Menurut saya, kebijakan afirmatif seharusnya cukup sampai tahap penyusunan dan pengajuan daftar bakal caleg oleh partai politik. Alasannya sederhana. Pertama, putusan MK sudah sangat jelas dan tegas dalam pertimbangannya bahwa penetapan caleg terpilih seharusnya dengan memperhatikan suara terbanyak, dan bukan dengan mempertimbangkan nomor urut dalam DCT. Putusan MK juga sama sekali tidak menyinggung bahwa penetapan dengan suara terbanyak itu harus memperhatikan kebijakan afirmatif.
Kedua, penetapan caleg terpilih dengan mengakomodir kebijakan afirmatif berpeluang menimbulkan perselisihan antar caleg dalam satu partai politik. Logikanya, caleg mana yang bersedia digantikan oleh caleg lain setelah mengetahui bahwa jerih payahnya berkampanye ternyata dapat menghasilkan satu kursi di DPR/DPRD. Perselisihan antar caleg ini dapat menghambat proses penetapan caleg terpilih, yang pada gilirannya dapat menghambat penyelesaian proses pemilu legislatif.
Ketiga, rasionalitas dalam memilih caleg menjadi tidak berlaku dengan kebijakan afirmatif itu. Logikanya, untuk apa pemilih bersusah payah mencari dan memilih caleg yang berkualitas apabila ternyata caleg yang dipilihnya itu mungkin tidak dapat menjadi anggota legislatif karena diganti oleh caleg lain berdasarkan kebijakan afirmatif.
Oleh karena itu, peraturan dalam bentuk apapun yang mengatur mengenai penetapan caleg terpilih seharusnya tetap mempertimbangkan suara terbanyak saja. Percayakan saja kepada pemilih untuk menggunakan hak pilihnya secara rasional. Kalau memang caleg perempuan yang diusulkan partai politik benar-benar berkualitas, maka pemilih tentu akan dengan sukarela memilihnya.
Pemilu sudah tinggal beberapa minggu lagi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih disibukkan dengan berbagai persiapan menjelang pemilu. Salah satunya adalah mempersiapkan peraturan dalam rangka menetapkan calon anggota legislatif (caleg) terpilih. Hal ini adalah sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 22-24/PUU-VI/2008, yang membuat Pasal 214 Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (UU Pemilu) menjadi tidak berlaku.
Pasal 214 tersebut pada dasarnya mengatur bahwa calon anggota DPR/DPRD terpilih ditetapkan dengan mempertimbangkan nomor urut dalam daftar calon tetap (DCT). Sehingga bagi caleg yang memiliki nomor urut paling kecil memiliki peluang besar untuk terpilih sebagai anggota legislatif dari partainya. Namun, dengan terbitnya putusan MK tersebut, yang mana MK memberikan pertimbangan bahwa penetapan anggota DPR/DPRD terpilih seharusnya berdasarkan pada perolehan suara terbanyak, maka penetapan caleg terpilih dengan mempertimbangkan nomor urut menjadi tidak berlaku lagi.
Kebijakan Afirmatif
Sebelum putusan MK tersebut terbit, UU Pemilu telah mengakomodir kebijakan afirmatif, yaitu memberikan aturan khusus dalam rangka mendorong partisipasi perempuan agar memiliki keterwakilan yang memadai dalam lembaga legislatif. Hal ini bisa terlihat dalam beberapa ketentuan UU Pemilu, yaitu antara lain: (i) mensyaratkan partai politik menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan di tingkat pusat agar dapat menjadi peserta pemilu; (ii) mensyaratkan partai politik mengajukan daftar bakal caleg yang memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan; dan (iii) nama-nama caleg dalam daftar bakal caleg tersebut disusun berdasarkan nomor urut dimana setiap 3 orang bakal caleg terdapat sekurang-kurangnya 1 orang bakal caleg perempuan.
Dengan begitu, apabila Pasal 214 UU Pemilu masih berlaku, banyak pihak menganggap bahwa caleg perempuan yang masuk dalam “tiga besar” nomor urut terkecil DCT punya peluang besar untuk terpilih sebagai anggota legislatif. Peluang ini menjadi tidak ada dengan terbitnya putusan MK tersebut. Bagi sebagian kalangan, dengan terbitnya putusan MK tersebut kebijakan afirmatif menjadi tidak ada artinya lagi.
Menanggapi hal itu, KPU bermaksud membuat peraturan mengenai penetapan caleg terpilih dengan tetap mengakomodir kebijakan afirmatif tersebut. Apabila kebijakan afirmatif diakomodir, maka jika ada satu partai politik meraih tiga kursi di suatu daerah pemilihan, kursi ketiga akan diserahkan kepada caleg perempuan.
Tetap Suara Terbanyak
Menurut saya, kebijakan afirmatif seharusnya cukup sampai tahap penyusunan dan pengajuan daftar bakal caleg oleh partai politik. Alasannya sederhana. Pertama, putusan MK sudah sangat jelas dan tegas dalam pertimbangannya bahwa penetapan caleg terpilih seharusnya dengan memperhatikan suara terbanyak, dan bukan dengan mempertimbangkan nomor urut dalam DCT. Putusan MK juga sama sekali tidak menyinggung bahwa penetapan dengan suara terbanyak itu harus memperhatikan kebijakan afirmatif.
Kedua, penetapan caleg terpilih dengan mengakomodir kebijakan afirmatif berpeluang menimbulkan perselisihan antar caleg dalam satu partai politik. Logikanya, caleg mana yang bersedia digantikan oleh caleg lain setelah mengetahui bahwa jerih payahnya berkampanye ternyata dapat menghasilkan satu kursi di DPR/DPRD. Perselisihan antar caleg ini dapat menghambat proses penetapan caleg terpilih, yang pada gilirannya dapat menghambat penyelesaian proses pemilu legislatif.
Ketiga, rasionalitas dalam memilih caleg menjadi tidak berlaku dengan kebijakan afirmatif itu. Logikanya, untuk apa pemilih bersusah payah mencari dan memilih caleg yang berkualitas apabila ternyata caleg yang dipilihnya itu mungkin tidak dapat menjadi anggota legislatif karena diganti oleh caleg lain berdasarkan kebijakan afirmatif.
Oleh karena itu, peraturan dalam bentuk apapun yang mengatur mengenai penetapan caleg terpilih seharusnya tetap mempertimbangkan suara terbanyak saja. Percayakan saja kepada pemilih untuk menggunakan hak pilihnya secara rasional. Kalau memang caleg perempuan yang diusulkan partai politik benar-benar berkualitas, maka pemilih tentu akan dengan sukarela memilihnya.
Apabila caleg perempuan merasa bahwa caleg laki-laki akan berbuat curang untuk menghalangi peluangnya menjadi anggota legislatif, maka laporkan saja kepada pihak yang berwenang. Dengan begitu, gender tidak perlu dijadikan keistimewaan untuk memperoleh kursi di DPR/DPRD. Yang penting adalah kualitas dari masing-masing caleg dan kepercayaan pemilih terhadap caleg yang bersangkutan.
Labels: caleg, DPR, DPRD, kebijakan afirmatif, KPU, Mahkamah Konstitusi, pemilu, politik, suara terbanyak


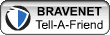
2 Comments:
belajar banyak
mengapa tidak:)
Post a Comment
<< Home